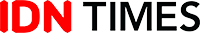[CERPEN] Tak Mungkin Ada yang Sempurna
![[CERPEN] Tak Mungkin Ada yang Sempurna](https://cdn.idntimes.com/content-images/community/2024/06/pexels-packermann-878151-3-d8c9e38e6cc180fefebd95071345491c-088b85dbcd15ee080c36d973c78b6216_600x400.jpg) ilustrasi lari pagi (pexels.com/Philip Ackermann)
ilustrasi lari pagi (pexels.com/Philip Ackermann)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Pukul delapan pagi. Tak ada yang lebih menyenangkan ketimbang jalan pagi di pinggir jalan raya, menuju stadion terdekat, lalu pulang. Hal itu sudah menjadi kebiasaan selama aku tinggal di kota ini. Berbulan-bulan yang kusorot hanyalah waktu yang kuhabiskan untuk jalan-jalan pagi. Sekarang aku tiba di titik jenuh. Bukan hanya jenuh pada kebiasaan ini, tapi juga pada kota ini.
Aku ingin pulang. Kembali tinggal bersama kedua orang tuaku. Menemani mereka setiap hari Minggu untuk bekerja bakti membersihkan belakang rumah atau menemani mereka untuk menonton pertandingan olah raga di televisi.
Aku spontan memberhentikan langkah. Sial, aku melewatkan minimarket itu. Terpaksa aku memutar langkah. Aku harus membeli air mineral. Lamunan pagi ini membuatku tidak fokus sama sekali.
Kembali berjalan, satu kilometer kemudian, tibalah di stadion. Ramai orang-orang yang tengah berlari. Ada juga yang berjalan santai. Biasanya aku langsung berjalan. Tapi, kali ini memilih untuk menepi. Mencari tempat untuk duduk dan meluruskan kaki. Pandanganku menatap sekeliling. Ada pasangan kekasih yang tengah berbincang manis sembari berjalan pelan. Kalau dilihat sekilas mereka adalah pasangan yang berkecukupan. Terlihat dari fisik serta setelan mereka.
Di arah jam sembilan, aku melihat ada seorang pemuda sedang berlari. Potongan rambutnya rapi. Sorot matanya terlihat tenang dan percaya diri. Lalu, radius tujuh meter di hadapanku, ada sebuah stand makanan. Pemiliknya sibuk melayani pesanan. Senyumnya tak memudar walau pelanggan tak memberikan waktu untuknya berhenti sejenak. Aku menghela napas. Orang-orang itu terlihat sempurna.
Kesempurnaan ingin aku raih. Makannya aku di sini. Makannya aku merantau karena aku ingin membenahi hidup. Perekonomian keluarga serta derajat orang tuaku harus membaik. Kerja dari pagi hingga sore, masih dilanjut kuliah di malam harinya, dan terkadang mengerjakkan side job juga. Aku banting tulang untuk ini. Setelah sibuk ini itu, aku ingin tidur, tetapi aku harus membersihkan kamar kos serta mencuci baju. Lelah, tapi sibuk memang yang aku mau. Sayangnya, setiap akhir pekan, aku baru merasa sepi. Setiap akhir pekan, perasaaan tentang asingnya kota ini semakin kentara jelas. Kesempurnaan batal aku miliki.
“Aw!”
Sebuah bola mengenai pundak kananku. Aku meraihnya sebelum bola itu menggelinding mengenai orang-orang yang lain. Lalu, ada seorang anak laki-laki datang menghampiriku.
“Kakak, maaf.” Ia menampakkan sederetan gigi putihnya. Mungkin ia berusia enam atau tujuh tahun. Aku tidak melihat ada tanda-tanda orang tuanya.
“Punyamu?”
Anak laki-laki berjersei Timnas Indonesia itu segera mengangguk. Ketika aku mau menyerahkannya, mataku tiba-tiba melihat sesuatu. Radius belasan meter dari belakang anak itu, ada sepasang suami-istri. Sang istri sedang mengerutkan keningnya.
“Ya, kan tadi aku nitip. Kamu yang harusnya tanggung jawab dong, bukan malah nyalahin aku!”
“Emang kamu tadi nggak lihat aku lagi ngobrol sama bosku? Harusnya kamu ajak Rey, bukan malah dititipin aku!”
“Kamu yang salah!”
“Enak aja.”
Aku membasahi bibir. Itu adalah mereka yang aku kata sepasang kekasih yang berkecukupan, ternyata mereka adalah sepasang suami istri.
“Kak?”
Editor’s picks
“Eh? Nama kamu Rey?”
“Kok tau?”
Aku segera berdiri. Menggandeng tangan anak itu dan segera menghampiri kedua orang tuanya. Seketika perdebatan mereka berhenti setelah melihat aku dan Rey berjalan mendekat. Sang ibu spontan meleluk, Rey kebingungan.
“Kenapa, Ma?”
“Kamu ke mana aja, Sayang?”
“Ambil bola.”
"Kenapa nggak izin dulu?”
“Papa lagi ngobrol, mau cari mama, tapi nggak tau mama di mana.”
Aku menarik senyum tipis. “Nih bola kamu,” ujarku sembari menyerahkannya kepada Rey. “Kakak duluan, ya.”
“Makasih, ya.” Kali ini Ibunya yang bersuara. Aku tersenyum saja dan berjalan menjauh.
Ada perasaan hampa yang hadir. Penilaianku terhadap mereka salah. Melihat perdebatan tadi, sepertinya mereka sering melakukannya. Berarti perbincangan manis yang kulihat tadi tidak abadi. Entah mengapa tiba-tiba aku kehilangan selera untuk berolah raga, aku ingin pulang.
***
Selesai. Aku menyelesaikan puzzle yang aku beli untuk mengusir rasa sepiku. Masih pukul empat sore. Aku sudah beli makanan untuk makan malam. Jadi tidak perlu keluar kamar hingga setidaknya besok pagi.
Aku memilih merebahkan tubuhku, meraih ponsel, dan membuka sosial media. Betapa terkejutnya ketika yang aku temukan pertama kali adalah berita seorang pria yang terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Video itu diambil tadi pagi. Sialnya adalah, orang itu sama dengan orang yang kulihat tadi. Ada sebuah akun yang mengomentari mengaku sebagai teman pria itu. Ia menjelaskan bahwa pria itu dilarikan ke rumah sakit karena terlalu berlebihan berolah raga karena ingin membuktikan kepada teman-teman lamanya bahwa ia dapat berubah. Ya Tuhan….
Aku mematikan ponsel dan memejamkan mata. Baru kali ini aku tidak fokus terhadap diriku sendiri. Hari ini aku memandang orang-orang, menatap sekeliling yang ternyata mereka tidak juga memiliki hidup yang sempurna. Apakah pemilik kedai makanan itu juga tidak sempurna? Apakah ia memiliki utang sehingga ia sibuk berjualan? Atau jangan-jangan ia juga sama seperti diriku yang ingin mengangkat perekonomian keluarga?
Maaf. Tuhan. Maaf.
Kesempurnaan itu memang tidak pernah ada. Hidup yang sempurna adalah mustahil. Memang hanya butuh "melihat" untuk menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Selama ini aku menutup mata dan enggan belajar dari lingkunganku. Aku tersadar bahawa dengan aku memforsir diri sendiri, tidak bersyukur, dan tidak pernah melihat orang lain justu mempresenetasikan bahwa kesempurnaan yang tidak pernah ada itu sangat jauh dari hidupku.
Baca Juga: [CERPEN] Cahaya Tersembunyi di Balik Kepalan Tangan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.