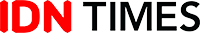[CERPEN] Tanah para Pecundang
![[CERPEN] Tanah para Pecundang](https://cdn.idntimes.com/content-images/community/2024/07/image-7d7419640aeb63c94761d54008d7c919_600x400.jpg) ilustrasi sungai (dok. Pribadi/ Adam Budiansyah)
ilustrasi sungai (dok. Pribadi/ Adam Budiansyah)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Di tepi barat Bukit Gondomayit, hiduplah Mada, seorang petani muda yang cekatan dan gagah, meski tak tampan. Ia sangat disiplin bak komando cadangan, setiap hari, Mada bangun saat fajar, menyiapkan peralatan lalu tenggelam menyibukkan diri di kebun warisan mertuanya. Setiap sore, setelah bekerja keras, Mada selalu singgah di warung kopi milik Mbak Yayuk. Warung itu terbuat dari batang dan anyaman bambu. Kini sedikit reot dengan beberapa lampu bercahaya kuning yang bohlamnya berdebu dan berdiri di bawah pohon bambu yang rimbun di tepi Sungai Bango yang dangkal. Meski begitu, warung ini selalu ramai oleh petani yang lelah dan bocah-bocah bolos pengajian mencari ikan dengan penuh harap saat sore.
Untuk mencapainya, orang-orang harus melewati jalan setapak beralas tanah yang bisa dilalui motor trail. Di depan warung, di tepi jalan setapak yang berbatasan langsung dengan Sungai Bango, terdapat bangku-bangku bambu. Itulah tempat favorit Mada untuk duduk dan memandangi sungai, ditemani riuh celometan Mbak Yayuk serta suara angin yang membenturkan daun-daun bambu bersautan dengan gemericik suara sungai. Di dalam sungai, gerombolan ikan gatul berbibir monyong berlalu-lalang, menunggu apes terjebak jaring bekas wadah nasi bocah-bocah setempat.
Pada sore itu, saat kabut tipis mulai turun dan suasana warung semakin riuh, Mada duduk di bangku favoritnya sambil merenung. Tiba-tiba terdengar suara deru motor trail dari kejauhan. Sahabatnya, Pala, muncul dengan motor trail odong-odong yang penuh dengan tali karet bekas ban dalam di beberapa bagiannya. Pala, dengan motor trail odong-odong yang penuh dengan tali karet bekas ban dalam di beberapa bagiannya, nyeletuk, "Mada, kawanku titisan Angrok, lagi-lagi kau melamun dalam keramaian. Memang apa sih yang kau lamunkan itu kawan?" tanyanya dengan nada celometan sembari menyeruput kopi hitam milik Mada tanpa izin, lalu mengangkat topi berlogo "M" ori seken warna ungu yang selalu dikenakannya setiap hari.
"Aku merenungi sifat bangsa ini, Pala," jawab Mada serius tanpa mengalihkan pandangan dari air sungai. "Orang-orang selalu berkata bahwa hidup ini hanya sementara. Tapi menurutku, mereka mengatakan itu hanya sebagai alasan karena takut berinovasi, dan bersembunyi dari kecemasan, cibiran, dan perubahan."
Pala menghela napas panjang, segera turun dari motor, memarkirkannya, memakai kembali topi ungunya, lalu ikut duduk memandangi air sungai. "Kau benar, Mada. Tapi bagaimana kita bisa mengubah cara pandang itu? Bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar?"
Di dekat mereka, seorang lelaki tua bernama Pak Honestian mendengarkan percakapan itu dengan seksama. Pak Honestian, yang sering duduk di warung kopi Mbak Yayuk pada sore hari, membawa segelas kopi panas yang baru diambilnya dari Mbak Yayuk dengan langkah pelan namun penuh kebijaksanaan. Ia menghirup aroma kopi sambil memperhatikan Mada dan Pala berbicara.
"Anak-anakku, kata-kata kalian mengingatkanku pada masa lalu. Hidup memang penuh ujian, tetapi di sanalah kita menemukan ketahanan sejati. Jangan terlalu banyak alasan," katanya dengan memancarkan aroma minyak Gandapura yang menyengat.
Editor’s picks
Pak Honestian duduk di samping mereka, matanya menerawang jauh pada kotoran manusia yang terlihat mengambang mulus di antara bebatuan. "Dulu, aku juga merasa takut, ragu, dan malu. Namun, aku memilih untuk berubah. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk melampaui batasan diri. Kalian harus menemukan tujuan yang jelas dalam hidup ini dan berjuanglah dengan segenap hati," katanya.
Mada mengangguk, menyadari bahwa fenomena seseorang seperti Pak Honestian yang tiba-tiba muncul lalu memberi nasihat merupakan salah satu dari "Indonesian Value". "Pak Honestian, bagaimana kita bisa tetap teguh di tengah badai tantangan? Apa yang harus kita lakukan supaya raga dan nyawa hasil pemberian Gusti Allah ini berguna?"
"Pertama-tama, kenali diri kalian lalu temukan tujuan yang membakar api jiwa," jawab Pak Honestian. "Kemudian, berinovasilah dan berjuang tanpa henti. Tancapkan kebiasaan untuk disiplin dan berevaluasi. Ingatlah, setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk mengukir namamu dalam sejarah, minimal sejarah bagi anak cucumu kelak."
Pala menatap Mada dengan mata berbinar. "Aku mengerti sekarang, Mada. Kita harus berani mengambil langkah, menghadapi ketakutan dan rasa malu akut, dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Kita lahir cuma sekali, mati pun cuma sekali. Waktu untuk hidup-lah yang berhari-hari, berkali-kali. Jadi, jangan sia-siakan nyawa pemberian Gusti Allah ini."
Mada tersenyum, matanya penuh dengan keyakinan baru. "Benar, Pala. Mari kita mulai sekarang. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kita tidak boleh membiarkan raga dan nyawa ini berlalu tanpa guna. Kita adalah pemroses takdir kita sendiri. Terlalu banyak waktu yang terbuang di negeri ini, sementara bangsa kita terus termarjinalkan dalam kebermanfaatan global. Kontras dengan sejarahnya yang kaya, kini, bangsa ini terjangkit wabah penakut dan pemalu massal, sehingga nyaris tidak mampu dan tidak mau berkontribusi dalam peradaban dunia. Yang lebih menjengkelkan, kita senang menjadikan kata-kata bijak sebagai tameng, tanpa menyadari bahwa semua itu menjadikan negeri ini tanah para pecundang."
Hari-hari berlalu, Mada dan Pala terus berinovasi dan berkolaborasi dalam mengolah sawah serta tegal, tanpa peduli cibiran orang. Mereka menghadapi setiap rintangan dengan keberanian, belajar dari setiap kegagalan, dan mencatat segala yang penting. Mereka juga bekerja sama dengan Nara, menantu tetangga yang seorang ilmuwan, untuk mengolah dan menerbitkan catatan-catatan mereka pada jurnal internasional terindeks. Mada dan Pala sering berdiskusi panjang lebar dengan Nara, merencanakan eksperimen dan inovasi baru yang dapat meningkatkan hasil panen mereka. Pak Honestian, dengan "Indonesian Value-nya", terus mengamati dan senantiasa memberi nasehat, menambah semangat mereka untuk terus berusaha.
Di masa tuanya, Mada dan Pala menganggur dengan bangga, menyadari bahwa mereka telah hidup sepenuhnya, tidak ada satu detik pun yang sia-sia. Kisah tentang Mada dan Pala menyebar ke seluruh negeri, menjadi legenda yang menginspirasi banyak orang. Mereka yang mendengar kisah itu diajak untuk berjuang melampaui batas diri, menghadapi kecemasan serta rasa malu dengan keberanian, dan mereka mengambil peran sebagai bagian dari bangsa yang senantiasa mengusahakan sumbangsih bagi peradaban dunia. Dan demikianlah, kehidupan di seluruh negeri berubah, atas nama tradisi, bangsa ini menjadi bangsa pemancing yang dikenal gemar mengenakan topi warna ungu.
Baca Juga: [CERPEN] Cahaya Tersembunyi di Balik Kepalan Tangan
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.